Hadiah Tahun Baru, Sengsaranya Rakyat Terus Diburu

Suara Netizen Indonesia, Tahun 2024 ditinggalkan, 2025 diharapkan banyak pihak bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Sayangnya tidak demikian. Meskipun pemerintah di awal tahun ini “memberikan hadiah istimewa” berupa pembatalan kenaikan PPN dari rencana 12 persen menjadi tetap 11 persen.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, presiden menerapkan PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah lanjut Budi (Beritasatu.com, 2-1-2025).
Budi Gunawan mengungkapkan, penetapan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas atau kaya. Sementara, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen. Maka rakyat tidak perlu khawatir. Karena pemerintah akan terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang semakin maju ke depannya.
Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024. Jelas saja memicu sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan penolakan dengan turun ke jalan.
Baca juga:
Nataru dan Bias Toleransi
Di antaranya ada aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) terdiri dari BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ), KBM STEI SEBI, HMI se-Jakarta dan Politeknik Negeri Media Kreatif menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Desember 2024 (Kontan.co.id, 30-12-2024).
Hingga muncul satu petisi yang meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN di laman change.org. Hingga Jumat pagi, 20 Desember 2024, petisi yang dibuat oleh Bareng Warga tersebut sudah ditandatangani oleh 145.362 orang. Menurut Bareng Warga, petisi ini dibuat karena kebijakan untuk menaikan PPN hanya akan membuat hidup masyarakat semakin sulit di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu (tirto.id, 21-12-2024).
Pajak dan Sistem Kapitalisme Gagal Mensejahterakan Rakyat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan pertimbangan kebijakan PPN akan dikenakan pada barang-barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN adalah karena, mayoritas kelompok paling kaya yakni desil 9 dan 10 paling banyak menikmati fasilitas pembebasan PPN ini, sekitar Rp 41.1 triliun. Sedangkan masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN.
“Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak pada kelompok yang lebih mampu. Oleh itu kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga,” tambah Sri Mulyani.
Inilah mengapa penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu. Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal.
Benarkah perhitungan Sri Mulyani ini? Dan mengapa selalu dikedepankan prinsip gotong royong dan keadilan. Karena faktanya, ketika tarif pajak kembali disesuaikan atau diharmonisasikan, keadaan rakyat secara mayoritas tak mengalami perubahan,bahkan terjadi pergeseran dimana kelas menengah menjadi miskin, kelas miskin menjadi kian miskin.
Baca juga:
Deklarasi Istiqlal, Latah Ala Kemenag
Bhima Yudhistira, ekonom sekaligus Executive Director Celios, mengatakan kenaikan PPN 12% tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak. “Hal itu terjadi karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omset pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain, seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai.”
Demikian pula menurut Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda dampak kenaikan tarif PPN per 2025 justru akan membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi negatif. “Ketika tarif PPN di angka 10 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 5 persen-an. Setelah tarif meningkat menjadi 11 persen terjadi perlambatan dari 4,9 persen (2022) menjadi 4,8 persen (2023). Diprediksi tahun 2024 semakin melambat.”
Huda menambahkan, penerimaan negara dengan adanya kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12% juga tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, yang patut diwaspadai adalah dampak psikologisnya terhadap daya beli masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi lebih besar. Data pertumbuhan pengeluaran konsumen untuk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) yang hanya naik 1,1 persen. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah. Kenaikan tarif pajak ini hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika Demikian, Mengapa Pajak Terus Ada ?
Perubahan tarif pajak ini sudah sesuai dengan keputusan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Sejumlah dalih diungkapkan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara. Kedua, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Ketiga, untuk menyesuaikan dengan standar internasional.
Pajak di Indonesia sudah ada sejak masa lalu, bahkan sejak masa klasik atau masa kerajaan. Sejumlah prasasti menyebut mengenai penarikan pajak yang berasal dari kerajaan masa Hindu-Buddha. Djoko Dwiyanto dalam “Pungutan Pajak dan Pembebasan Usaha di Jawa pada Abad IX-XV Masehi” yang terbit dalam Humaniora (No.1, 1995), ada beberapa jenis pajak yang disebut dalam prasasti, seperti pajak tanah, pajak perdagangan, pajak orang asing, dan pajak keluar masuk wilayah.
Setelah era klasik, di masa kolonial pajak juga menjadi salah satu pemasukan bagi negara. Kompeni atau VOC menerapkan beberapa kebijakan pajak, salah satunya contingenten atau pajak hasil bumi. Kemudian masa penjajahan Inggris juga menetapkan pajak, di antaranya pajak tanah atau landrent yang diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles. Dengan menguasai Indonesia, berarti Inggris menganggap semua tanah adalah milik negara.
Lantas adakah negara yang mampu tegak tanpa pendapatan pajak? Tentu saja ada, negara tersebut akan mengoptimalkan pendapatan negara dari sisi selain pajak, yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Contoh tambang nikel, Indonesia memiliki cadangan yang melimpah, 23 persen dari total cadangan dunia.
Contohnya Tambang Sorowako, salah satu tambang nikel terbesar di Sulawesi yang kuasai oleh PT Vale Indonesia, anak perusahaan dari Vale S.A., yang berkantor pusat di Brasil. Tahun 2023, tambang ini memproduksi sekitar 70.728 metrik ton nikel. Dan berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar US$1,23 miliar atau sekitar Rp19,23 triliun (estimasi kurs Rp15.611) di tahun 2023. Dengan laba bersih mencapai US$274,33 juta atau sekitar Rp4,29 triliun. (Bisnis market).
Estimasi ini baru dari satu tambang, data dari Kementerian ESDM, ada 1.215 WPR, sekitar seribu tambang batubara yang terdaftar, dan ratusan tambang lain dengan kapasitas produksi sangat besar. Belum lagi kalau kita berbicara tentang potensi laut dan agraria Indonesia.
Jika negara saja yang mengelola, kemudian dikembalikan hasil pemanfaatannya kepada rakyat sudah pasti akan memenuhi brankas pendapatan negara lebih dari cukup bahkan angkanya bisa melampaui nilai perolehan pajak.
Sayangnya, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara dalam sistem Kapitalisme. Indonesia termasuk yang menerapkan sistem rusak ini. Meski kekayaan alamnya melimpah namun tak berdaulat mengelola sendiri. Karena itu pajak adalah satu keniscayaan, demikian pula kenaikan besaran pajak dan beragam jenis pungutan pajak.
Baca juga:
Terowongan Simbol Toleran, Benarkah Dibutuhkan?
Ketika pajak menjadi sumber pendapatan negara, maka hakekatnya rakyat membiayai sendiri kebutuhannya akan berbagai layanan yang dibutuhkan. Dengan kata lain negara tidak berperan sebagai pengurus rakyat, melaonkan hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator, melayani kepentingan para pemilik modal. Rakyat biasa akan terabaikan.
Kejinya, rakyat menjadi sasaran berbagai pungutan negara yang bersifat ‘wajib’ sebagai konsekuensi posisinya sebagai warga negara. Pungutan pajak jelas menyengsarakan rakyat, bahkan negara bak vampir yang digambarkan di Eropa masa klasik, menghisap darah manusia agar tetap bertahan hidup. Apalagi pungutan itu tidak memandang kondisi rakyat. Sekaligus bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Bagaimana kelak pertanggungjawaban para pemimpin ini di akhirat jika tidak segera bertaubat? Mirisnya, malah semakin banyak kebijakan pajak yang memberikan keringanan pada para pengusaha, dengan alasan untuk meningkatkan investasi pengusaha bermodal besar. Asumsinya investasi akan membuka lapangan kerja dan bermanfaat untuk rakyat. Padahal faktanya tidak seperti itu. Rakyat tetap kelimpungan mencari kerja, jika pun sudah bekerja, masih harus mencari tambahan sebab tak mencukupi kebutuhan dasarnya.
Sistem Islam Mewujudkan Negara Tanpa Pajak
Jadi, adakah negara yang mampu tegak berdiri, mandiri sekaligus mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya? Ada, yaitu negara yang hanya menerapkan syariat Allah sebagai asas pengaturannya.
Hal ini karena Islam memandang pajak , yang dalam Islam disebut Dharibah, hanya sebagai alternatif terakhir sumber pendapatan negara, itu pun hanya dalam konsisi tertentu, dan hanya pada kalangan tertentu. Islam memiliki sumber pendapatan yang banyak dan beragam. Dan dengan pengaturan sistem politik dan ekonomi Islam, khilafah akan mampu menjamin kesehateraan rakyat individu per individu.
Menurut Zallum (2003), pos pendapatan APBN Khilafah terdiri dari 12 jenis, yakni pendapatan dari harta rampasan perang (anfal, ganimah, fai, dan khumus); pungutan dari tanah yang berstatus kharaj; jizyah (pungutan dari nonmuslim yang tinggal di negara Islam); harta milik umum; harta milik negara; ‘usyur (harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri); harta tidak sah para penguasa dan pegawai negara atau harta hasil kerja yang tidak diizinkan syarak; khumus barang temuan dan barang tambang; harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris; harta orang-orang murtad; dharibah; dan harta zakat. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah).
Sehingga praktis, sumber APBN Khilafah atau kas baitulmal sama sekali tidak bergantung pada sektor pajak. Dan samasekali tidak bisa disamakan APBN ala kapitalisme. Islam juga menetapkan penguasa sebagai rain (pengurus urusan rakyat) dan junnah ( pelindung), dan mengharamkan penguasa untuk menyentuh harta rakyat.
Konteks “negara tidak menyentuh harta milik umum” dimaknai oleh Syaikh Atha’ bin Khalil Abu Ar-Rasytah, dalam kitab beliau Al Amwal fii Daulah Khilafah, bahwa pemasukan dan pengeluaran negara yang ditetapkan syara’ tidak berbasis pajak dan utang.
Artinya, dalam penerapan sistem ekonomi Islam oleh negara (Khilafah), pajak tidak menjadi sumber pemasukan utama negara. Tidak ada beban wajib pajak bagi kaum Muslimin. Kewajiban penguasa mengelola harta rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas umum dan layanan yang akan memudahkan hidup rakyat. Sungguh, secara fitrah kapitalisme sudah tidak sesuai sebab menimbulkan kekejian, saatnya kembali kepada pengaturan Islam. Wallahualam bissawab. [SNI].







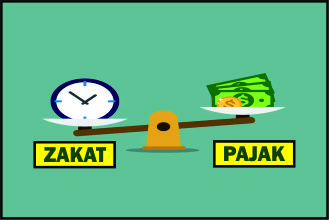



Komentar